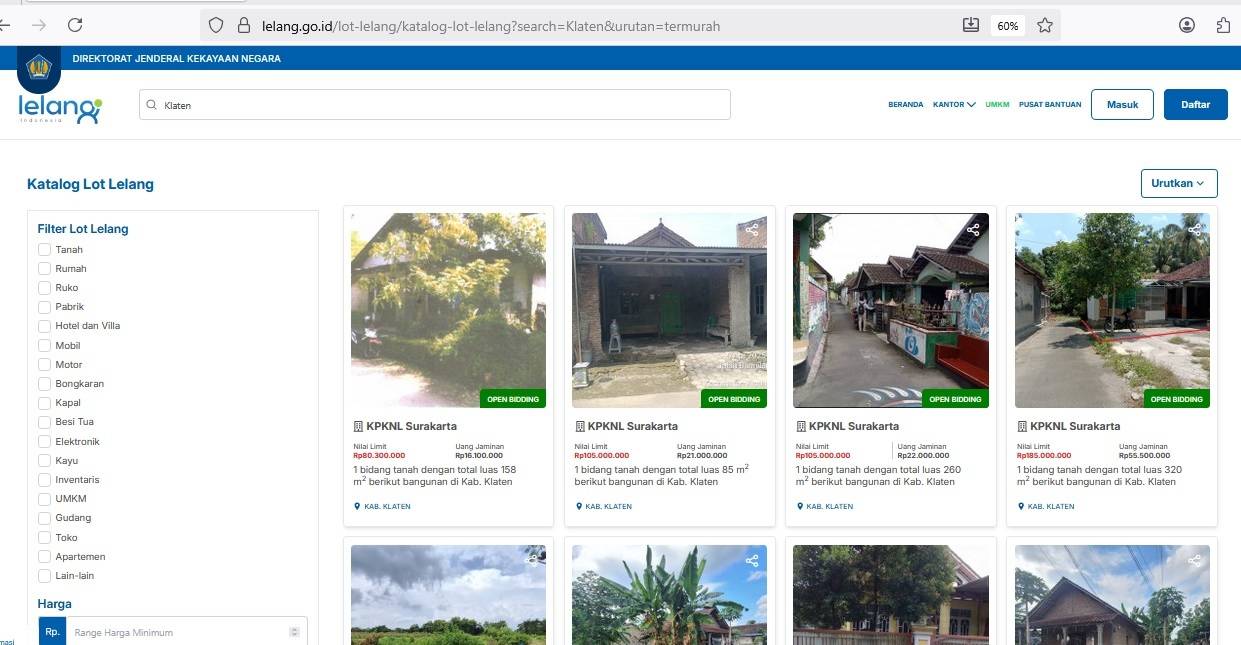MASIH hangat dalam ingatan kita, geger Pati ketika sekitar 50.000 warga di tanah Pantura itu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 lalu.
Aksi tersebut dipicu rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang nilainya mencapai 250 persen. Ironisnya, kebijakan yang begitu memberatkan itu diumumkan nyaris tanpa komunikasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
Bupati Pati, Sudewo, berdalih bahwa potensi PBB di daerahnya masih kecil dan sudah 14 tahun belum pernah mengalami kenaikan. Ia membandingkan dengan kabupaten tetangga: Jepara mampu meraup Rp 75 miliar, Rembang Rp 50 miliar, dan Kudus Rp 50 miliar, sementara Pati hanya Rp 29 miliar. Padahal, menurutnya, luas dan besarnya Kabupaten Pati tidak kalah dari daerah-daerah tersebut.
Namun alasan itu tidak mampu meredam keresahan publik. Keresahan itu mengerucut menjadi ancaman untuk melakukan demo besar-besaran. Bupati Sudewo bahkan masih sempat menantang rakyatanya sendiri untuk melakukan aksi demo. Kalau perlu, lima puluh ribu rakyat demo ia tak akan mundur.
Namun ketika suasana semakin memanas, Bupati Sudewo membatalkan rencana kenaikan pajak tersebut. Ibarat nasi telah menjadi bubur, pembatalan itu tak cukup untuk menenangkan warga, karena kemarahan warga sudah sampai pada puncaknya, dan aksi tetap terjadi pada 13 Agustus 2025. Tuntutan bergeser, dari semula menuntut penurunan pajak, menjadi pemakzulan Bupati Sudewo.
Di tengah aksi demonstrasi yang sedang berlagsung, Bupati Sudewo bahkan dilempari sandal dan botol air mineral saat meminta maaf dari atas mobil water canon. Sikap yang terlambat, rakyat sudah keburu murka, dengan meneriakkan turunnya sang bupati.
Nasib Sudewo benar-benar ibarat telur di ujung tanduk. DPRD Pati menerima tuntutan warga dan sepakat menggunakan hak angket untuk memproses pemakzulan sang bupati. Sebuah drama politik yang berawal dari urusan pajak daerah dan berakhir pada bakal terpuruknya seorang Bupati dari jabatannya hanya karena salah bersikap.
Pati dan Solo
Bicara soal “geber menggeber pajak”, tak perlu jauh-jauh ke Pati. Di Kota Solo pun, di awal tahun 2023, ketika menjabat sebagai Walikota, Gibran Rakabuming Raka pernah menaikkan tarif PBB hingga 300–400 persen. Sama seperti Pati, kenaikan itu diumumkan tanpa sosialisasi memadai. Tagihan warga tiba-tiba melonjak drastis: ada yang tadinya Rp 700.000 mendadak menjadi Rp 2,2 juta, bahkan ada yang harus membayar puluhan juta rupiah.
Tentu saja warga Solo terkejut. Aduan membanjiri kanal pengaduan resmi (ULAS) dan DPRD pun bereaksi keras. Namun, berbeda dengan Pati, gejolak itu tak sampai pecah menjadi aksi massa di jalanan. Mengapa? Karena Gibran cepat mengoreksi. Hanya dalam hitungan hari setelah keluhan menguat, ia langsung membatalkan kenaikan, mengembalikan tarif ke angka tahun sebelumnya, bahkan menjanjikan restitusi bagi warga yang sudah telanjur membayar.
Nah, di sinilah menariknya: sama-sama menaikkan pajak dalam jumlah fantastis, sama-sama tanpa sosialisasi, dan sama-sama kemudian dibatalkan. Tetapi respons masyarakat ternyata sangat berbeda. Solo adem ayem, sementara Pati bergolak hebat hingga berujung tuntutan pemakzulan.
Apa yang membedakan keduanya?
Pertama, soal kecepatan respons. Gibran bergerak cepat memotong krisis sebelum meluas. Sementara di Pati, pembatalan datang terlambat, setelah keresahan berubah jadi amarah kolektif.
Kedua, saluran aspirasi. Warga Solo punya kanal formal seperti ULAS, juga DPRD yang sigap menyuarakan penolakan. Warga merasa suaranya tersalurkan. Di Pati, aspirasi publik tidak menemukan jalur yang efektif, sehingga langsung meluber ke jalan.
Ketiga, figur dan konteks politik. Gibran bukan sekadar Walikota, ia juga putra presiden aktif. Posisi itu membuat banyak pihak, termasuk elite politik dan sebagian warga, masih memberi “toleransi”. Kritik tetap ada, tapi lebih terkendali. Sementara Sudewo hanyalah bupati lokal yang belum punya jejaring politik nasional sekuat itu, sehingga lebih mudah dijadikan sasaran kemarahan publik.
Keempat, budaya politik lokal. Solo dengan kultur urban lebih terbiasa menyalurkan aspirasi lewat mekanisme formal. Sedangkan di Pati, dengan basis sosial pedesaan yang kuat, tradisi “ngluruk bareng” lebih hidup. Ketika ada ketidakadilan, warga cenderung bergerak bersama ke jalan.
Kasus ini mengajarkan satu hal sederhana: dalam kebijakan publik, bukan hanya isi kebijakan yang penting, tetapi juga bagaimana cara pemerintah mengkomunikasikan dan merespons aspirasi rakyat dengan baik dan tepat.
Kenaikan pajak bisa diterima jika transparan, proporsional, dan dikomunikasikan dengan baik. Tetapi kebijakan yang terburu-buru, tanpa sosialisasi, apalagi tanpa empati, hanya akan melahirkan keresahan. Dan dalam konteks tertentu, keresahan itu bisa meledak jadi gejolak sosial, bahkan mengancam legitimasi pemimpin itu sendiri. [*]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.

 2 months ago
36
2 months ago
36