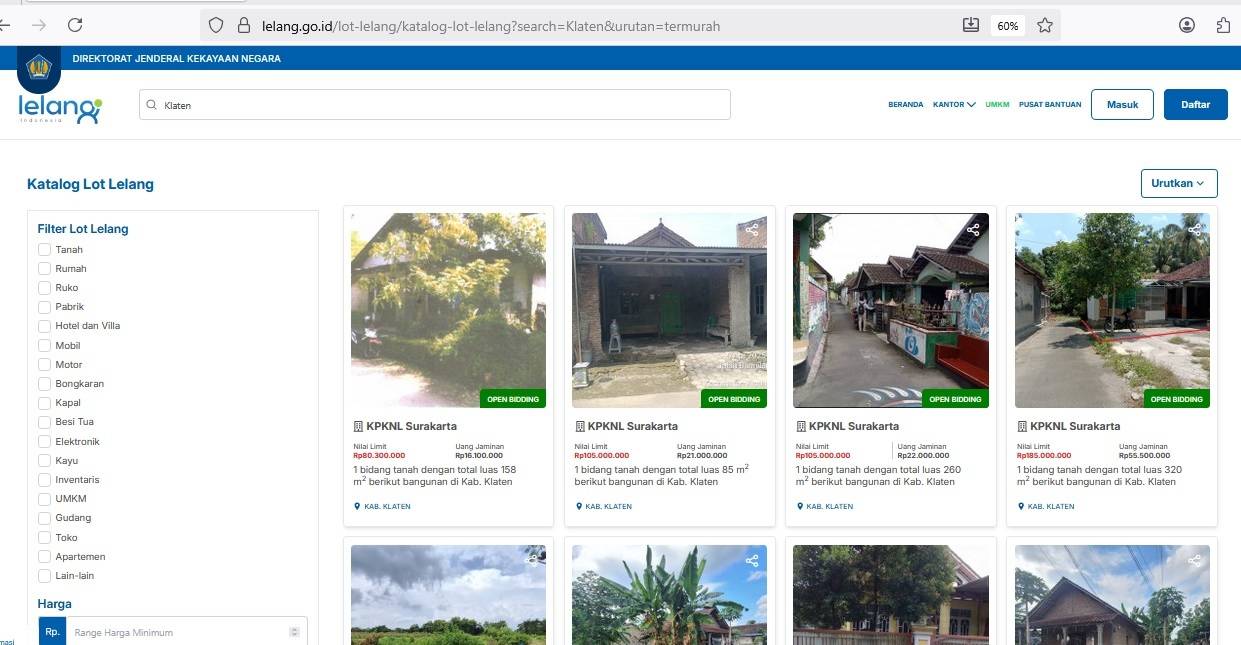Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak awal mengusung semboyan partainya anak muda. Belakangan, sejak berembus isu kemungkinan berlabuhnya mantan Presiden Joko Widodo ke partai tersebut, berkembang wacana mengenai partai super terbuka.
Narasi yang dibangun adalah partai yang masih berlogo bunga mawar tersebut adalah milik bersama, tanpa sekat-sekat elitis, tanpa patronase keluarga. Semua kader adalah pemilik saham dengan porsi yang setara.
Namun, di balik semangat kesetaraan itu, sekarang publik justru dihadapkan pada sebuah ironi: partai yang secara patron antidinasti, secara tak langsung justru semakin lekat dengan simbol dinasti politik itu sendiri, yakni keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Anggapan tersebut diperkuat dengan pernyataan pendiri PSI, Jeffrie Geovanie, yang menyebut bahwa PSI harus mendapatkan darah Jokowi. Pernyataan yang secara jelas faktual menampar logika publik. Bukan hanya karena frasa “darah” itu sendiri mencerminkan pendekatan politik yang beraroma feodal, tapi juga karena hal itu mengkhianati semangat meritokrasi yang konon menjadi fondasi partai tersebut.
Jika benar PSI “harus” memiliki darah Jokowi, atau – sebagaimana diucapkan Jeffrie Geovanie — kalau tak mendapat darah keluarga Jokowi partai tersebut tutup, maka semakin jelas menunjukkan bahwa PSI sejatinya bukan partai ide, melainkan partai keluarga—meski bukan keluarganya dari pendiri resmi.
Terlebih lagi dengan munculnya kabar bahwa mantan Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Penasehat PSI, maka lengkaplah potret politik gaya baru versi PSI, yang sejatinya hanya daur ulang dari partai masa lalu.
Politik karismatik yang dibungkus jargon anak muda, dan sempat menarik simpati publik, ternyata lambat laun semangatnya mengarah ke aura feodalistik. Usai kongres perdananya pada Minggu (20/7/2025), PSI justru menghadapi ujian identitas. Di satu sisi, mereka ingin tampil progresif dan berani menantang oligarki. Di sisi lain, mereka tampak “menjual nama besar” Jokowi sebagai tiket masuk ke ruang kekuasaan demi meraih kursih senayan.
Pernyataan pendiri PSI dimana kalau sampai gagal mendapatkan darah Jokowi, PSI lebih baik tutup saja, membuat publik semakin “bingung” untuk membaca konsep kepartaian dari PSI. Bukan karena tidak ada kader potensial di partai tersebut, tapi karena konsep dan arah perjuangannya yang terkesan makin kabur.
Yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar keberpihakan pada satu figur, tapi hilangnya ruang berpikir rasional dalam membangun partai. Ketika partai dibangun bukan atas dasar ideologi dan basis rakyat, melainkan pada figur semata, maka lahirlah partai-partai semu—yang hidup dari popularitas, dan bukan dari gagasan.
PSI seharusnya belajar dari sejarah: partai-partai yang menjadikan satu keluarga sebagai poros, umumnya tak mampu bertahan lama ketika figur itu pensiun atau gagal menjaga simpati publik. Jika benar PSI tak bisa hidup tanpa Jokowi dan keluarganya, maka apa bedanya dengan partai dinasti yang mereka kritik dulu? [*]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.

 3 months ago
44
3 months ago
44