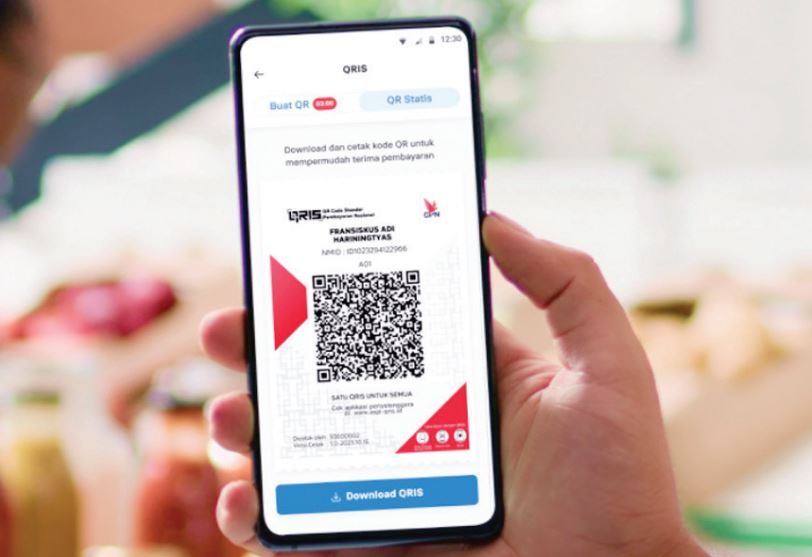Ilustrasi wanita hamil. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa ada petuah atau gugon tuhon, wanita yang sedang hamil dilarang mengalungkan handuk di leher karena bisa berakibat bayi di dalam kandungannya terlilit usus | Foto ilustrasi: Freepik
Ilustrasi wanita hamil. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa ada petuah atau gugon tuhon, wanita yang sedang hamil dilarang mengalungkan handuk di leher karena bisa berakibat bayi di dalam kandungannya terlilit usus | Foto ilustrasi: FreepikJOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah derasnya arus modernisasi dan logika rasional yang kian mengakar, warisan budaya berupa gugon tuhon kian terpinggirkan. Gugon tuhon, yang dalam budaya Jawa dimaknai sebagai pantangan atau merupakan petuah leluhur, sejatinya bukan sekadar mitos tak berdasar.
Namun, ia adalah sebuah refleksi kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang, untuk menjaga harmoni kehidupan. Meskipun, tentu saja, hal itu tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.
Barangkali di berbagai daerah di Jawa ini, warisan tersebut masih berdenyut hingga sekarang, meski kadarnya perlahan. Sebagian masyarakat masih memegang teguh ajaran-ajaran leluhur tersebut, meski tak sedikit pula yang mulai meninggalkannya. Sebuah penelitian di daerah Lumajang oleh Siti Nurhidayati dari Universitas Negeri Jember (Unej), sebagai contoh, memberikan gambaran adanya gejala degradasi terhadap warisan nenek moyang tersebut.
Penelitian yang dilakukan terhadap dua belas informan di wilayah ini mengungkapkan beragam respons terhadap gugon tuhon: dari yang memahami dan memercayai, hingga yang bersikap skeptis dan tak lagi mau menjalankannya.
Ada tiga jenis gugon tuhon yang masih dikenal masyarakat Tompokersan, Lumajang. Pertama, gugon tuhon kang salugu, yakni pantang larang yang berkaitan langsung antara orang tua dan anak. Kedua, wasita sinandi, petuah yang dibungkus dalam kalimat simbolik dan samar. Dan ketiga, pepali atau wewaler, berupa larangan tegas untuk tidak melakukan sesuatu karena diyakini dapat mendatangkan kesialan.
Contoh sederhana namun menggelitik antara lain misalnya: Wanita hamil dilarang melilitkan handuk di leher (bisa menyebabkan bayi terlilit usus). Saat hamil, suami istri dilarang berkata jorok atau menghina orang lain (karena bisa tumus, atau berakibat tidak baik bagi bayi).
Beberapa contoh gugon tuhon lainnya yang masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa antara lain: larangan duduk di atas bantal (dipercaya dapat menyebabkan borok di bagian bokong), Anak gadis tidak boleh makan di tengah pintu (bisa menghambat datangnya jodoh), Kalau makan jangan sampai disisakan karena konon bisa membuat ayam peliharaan mati.
Meskipun terdengar sederhana dan bahkan tak masuk akal bagi sebagian orang, gugon tuhon semacam ini sesungguhnya menyimpan pesan simbolis yang mengajarkan etika, sopan santun, dan kesadaran sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Dari beragam bentuk gugon tuhon yang diwariskan turun-temurun, sebagian di antaranya ternyata masih sangat relevan dengan nilai-nilai kehidupan masa kini. Kita ambil salah satu contoh petuah: “Kalau makan jangan sampai ada sisa.”
Di balik larangan-larangan sederhana ini, sejatinya tersimpan pesan moral yang dalam tentang kesadaran sosial dan etika hidup. Petuah seperti tidak menyisakan makanan, misalnya, mengajarkan kita untuk menghargai setiap rezeki yang ada, karena di luar sana masih banyak orang yang hidup dalam keterbatasan dan kesulitan untuk sekadar mengisi perut. Maka, menyisakan atau membuang makanan bukan hanya soal pemborosan, tetapi juga mencerminkan kurangnya empati terhadap sesama.
Meski demikian, di telinga generasi milenial masa kini, contoh-contoh gugon tuhon seperti ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi petuah leluhur, larangan-larangan tersebut tetap diindahkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang telah mengakar dalam budaya. Lebih dari sekadar warisan tutur, gugon tuhon sesungguhnya mengandung pesan yang lebih dalam.
Menariknya, gugon tuhon tidak hanya menyampaikan larangan, tapi juga memiliki makna ilokusi—pesan atau maksud yang ingin disampaikan—dan efek perlokusi, yakni dampak terhadap perilaku masyarakat. Artinya, petuah warisan nenek moyang itu bukan sekadar mitos kosong, melainkan mengandung fungsi sosial sebagai penuntun etika dan pengingat akan nilai-nilai hidup.
Memang tak bisa dipugkiri, gugon tuhon yang bersifat “mengancam” tanpa dasar logis, akhirnya secara perlahan-lahan memang mulai ditinggalkan. Di era ketika setiap informasi bisa diverifikasi dengan cepat, ancaman yang tak masuk akal mulai kehilangan daya tawarnya. Kepercayaan tak lagi bisa berjalan sendiri tanpa pendampingan dari pengetahuan yang masuk akal.
Tapi, mungkinkah gugon tuhon benar-benar bakal usang dan hilang?
Gugon tuhon barangkali mengalami degradasi seiring laju kemajuan zaman, namun bukan berarti akan lenyap sepenuhnya. Sebab pada hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih dapat diselaraskan dengan konteks kehidupan masa kini.
Ia tetap relevan jika dilihat sebagai simbol penghormatan terhadap masa lalu dan identitas kultural. Gugon tuhon adalah jendela yang memperlihatkan bagaimana masyarakat dulu membangun tatanan sosial, menyisipkan moral dalam narasi sederhana, dan menjaga ketertiban dalam bentuk petuah.
Di tengah zaman yang serba digital, ketika generasi muda lebih akrab dengan algoritma daripada petuah simbah (nenek moyang), petuah luhur itu tetap menyimpan makna penting—bukan untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk dipahami konteks dan pesan moralnya.
Mungkin sudah saatnya kita tidak lagi hanya menertawakan atau membuang gugon tuhon, melainkan merangkainya ulang dalam bentuk yang lebih kontekstual. Sebab, di balik setiap petuah leluhur, senantiasa tersimpan niat luhur, yakni agar manusia hidup lebih berhati-hati, lebih sopan, dan tidak melupakan akar dan asal-usulnya. Begitulah kira-kira. [Hamdani MW]
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.

 3 months ago
40
3 months ago
40