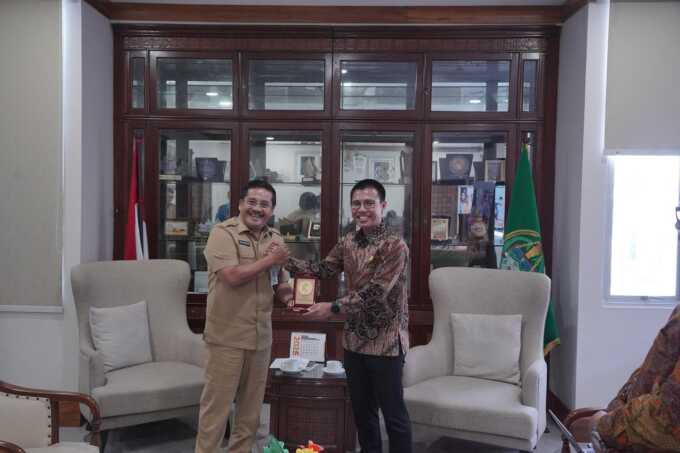Setiap hari, puluhan ribu keluarga di Indonesia berhadapan dengan penyakit yang diam-diam menggerogoti hidup: jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, dan diabetes. Penyakit-penyakit ini dikenal sebagai penyakit katastropik yang bersifat kronis, progresif, mahal, dan berisiko menyebabkan kematian dini atau disabilitas.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasien, tapi juga menghancurkan pendapatan keluarga, menurunkan produktivitas nasional, dan membebani anggaran kesehatan negara. Bahkan, tak sedikit yang jatuh miskin karena biaya berobat yang tinggi. Inilah penyebab utama kematian di dunia, dan tekanan ganda ini memukul sistem kesehatan kita yang sudah lelah menghadapi beban penyakit menular dan tidak menular sekaligus. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang bertanggung jawab, tapi kapan kita akan mulai bergerak bersama.
Masalah ini bukan sebatas isu medis atau angka statistik semata. Di balik data yang terlihat teknis, ada kenyataan getir yang dialami puluhan ribu keluarga setiap harinya. Penyakit katastropik kini menjadi beban struktural dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan tahun 2024, tercatat lebih dari 33 juta kasus penyakit katastropik dengan total biaya klaim mencapai Rp37,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung menjadi penyumbang beban terbesar, menghabiskan lebih dari Rp19 triliun, disusul oleh kanker dan gagal ginjal kronis. Namun, di balik angka-angka besar itu, tersimpan ironi: program pencegahan berjalan lambat, koordinasi antar profesi minim, dan pasien kerap baru tertangani saat komplikasi telah terjadi.
Di lapangan, tantangan utamanya bukan semata kurangnya alat atau fasilitas, melainkan gagalnya sistem bekerja sebagai tim. Dokter bekerja sendiri, perawat tenggelam dalam administrasi, ahli gizi hanya sesekali diminta konsultasi, dan promosi kesehatan lebih sering jadi lampiran program ketimbang inti layanan. Sistem rujukan pun masih bersifat administratif alih-alih klinis-strategis.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antarprofesi atau Interprofessional Collaboration (IPC) belum menjadi budaya kerja. Lebih parahnya lagi, kegagalan ini sudah dimulai sejak bangku pendidikan. Mahasiswa kedokteran, keperawatan, farmasi, gizi, dan kesehatan masyarakat masih belajar dalam silo masing-masing. Mereka tidak diberikan ruang untuk memahami peran satu sama lain dalam menangani satu pasien atau satu keluarga secara komprehensif. Maka tidak mengherankan ketika mereka memasuki dunia kerja, kolaborasi lintas profesi terasa asing dan tidak terbentuk secara alamiah.
Refleksi Kolektif dari Lingkar Ahli Kesehatan Masyarakat
Dalam momentum 1st INTERNATIONAL CONFERENCE yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dengan tema “Strengthening Interprofessional Collaboration in the Management of Catastrophic Diseases Using Primary Care Integration Approach”, para peserta dan narasumber dari berbagai latar belakang profesi kesehatan berkumpul untuk menggali peran kolaboratif dalam menanggulangi penyakit katastropik.
Salah satu sesi khusus dalam konferensi ini mengangkat topik “How can Public Health Experts Contribute to Catastrophic Diseases Management”, yang memicu refleksi mendalam, khususnya dari kalangan anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Pengda Sumatera Utara.
Awalnya, semangat peserta sangat tinggi untuk menegaskan bahwa profesi kesehatan masyarakat memiliki kontribusi sentral dalam pendekatan promotif dan preventif.
Ada kepercayaan bahwa keahlian dalam edukasi kesehatan, advokasi, dan perencanaan program adalah fondasi utama dalam mencegah beban penyakit katastropik yang terus meningkat. Namun, pandangan ini diuji saat data lapangan dipaparkan secara terbuka.
Program strategis seperti pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari quick win Prabowo–Gibran dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dijalankan oleh dokter dan tenaga kesehatan (named dan nakes) menunjukkan realisasi yang belum optimal di berbagai daerah.
Kunjungan masyarakat ke layanan primer masih di bawah harapan, memperlihatkan bahwa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan belum tumbuh merata. Yang lebih menggelitik kesadaran, kontribusi profesi kesehatan masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku kolektif belum sepenuhnya menjangkau akar permasalahan.
Pengalaman ini menyadarkan bahwa sebesar apa pun kontribusi keilmuan Kesehatan masyarakat dalam promotif dan preventif, hasilnya akan terbatas jika dijalankan secara terpisah. Interprofesionalisme bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan nyata dalam menghadapi kompleksitas penyakit katastropik. Kolaborasi antara dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, tenaga promosi kesehatan, dan pembuat kebijakan harus dibangun sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Masyarakat pun tidak dapat diposisikan sekadar sebagai penerima, tetapi mitra aktif dalam sistem kesehatan.
Refleksi ini memperkuat komitmen bahwa membangun sistem kesehatan nasional yang tangguh haruslah berbasis kolaborasi lintas profesi yang setara dan saling melengkapi. Tidak lagi mencari siapa yang paling berjasa, tetapi siapa yang bersedia berjalan bersama untuk menciptakan layanan kesehatan primer yang kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan dan berpihak pada kesehatan masyarakat secara nyata.
Pentingnya IPC
Penyakit katastropik seperti jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, dan diabetes bukan hanya penyakit individu, tetapi masalah sistemik yang menyentuh dimensi medis, sosial, dan ekonomi. Bebannya tidak bisa diatasi oleh satu profesi atau pendekatan klinis semata. Menurut WHO (2023), lebih dari 60% intervensi kronik yang berhasil bersifat kolaboratif, berbasis komunitas, dan melibatkan tim lintas profesi.
Ini menunjukkan bahwa Interprofessional Collaboration (IPC)bukan pilihan tambahan, melainkan fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang efektif dan tangguh menghadapi kompleksitas penyakit katastropik.
Secara teoritis, Social Ecological Model (McLeroy et al., 1988) menekankan bahwa perilaku dan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi antar level yaitu individu, komunitas, organisasi, dan kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi tidak hanya dibutuhkan oleh antarprofesi kesehatan, tapi juga lintas sektor.
WHO juga memperkenalkan Interprofessional Collaborative Practice Framework (2010), yang menegaskan bahwa kolaborasi memperkuat kepuasan pasien, efisiensi sistem, dan hasil Kesehatan terutama dalam bentuk pelayanan primer dan pengendalian penyakit kronis. Tanpa kolaborasi, yang terjadi adalah fragmentasi peran, duplikasi layanan, dan pemborosan sumber daya.
Sejumlah negara telah membuktikan efektivitas IPC. Di Thailand, tim interprofesi di layanan primer yang terdiri dari dokter keluarga, perawat komunitas, ahli gizi, dan kader kesehatan mampu menurunkan komplikasi diabetes dan hipertensi hingga 40% (Noknoy, 2020). Australia dan Inggris menerapkan model Community Health Hub yang mengintegrasikan layanan medis, farmasi, rehabilitasi, dan promosi kesehatan dalam satu sistem, terbukti meningkatkan efektivitas layanan primer (Bambra et al., 2016). Di Brasil, Family Health Strategy yang melibatkan tim multidisipliner berbasis komunitas berhasil menurunkan rawat inap akibat penyakit kronik sebesar 24% dalam lima tahun (Macinko et al., 2018).
Indonesia sendiri telah memulai langkah awal melalui program PIS-PK dan integrasi layanan primer (ILP). Namun, tantangan masih besar. Studi BPJS Kesehatan (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 35% klaim JKN berasal dari penyakit katastropik, yang sebagian besar ditangani di FKTP tanpa koordinasi lintas profesi yang optimal. Program IPE (Interprofessional Education) yang dipelopori UGM dan Kemenkes menunjukkan hasil positif dalam membentuk kesiapan kolaboratif mahasiswa kesehatan (UGM, 2021), namun belum merata di seluruh institusi pendidikan. Untuk mengatasi penyakit katastropik, kita tidak hanya butuh dokter yang hebat atau program yang terstruktur, tetapi tim yang solid, saling mengisi dan bekerja dengan visi yang sama.
IPC dan Katastropik
Penyakit katastropik menuntut penanganan yang tidak bisa dilakukan secara individu-profesi, melainkan melalui kolaborasi tim yang terstruktur. Di tingkat layanan primer, IPC dimulai dari deteksi dini yang melibatkan berbagai peran: dokter sebagai ujung tombak diagnosis, perawat dalam pemantauan klinis, ahli gizi untuk modifikasi gaya hidup, dan tenaga promosi kesehatan sebagai penggerak perubahan perilaku.
Di daerah terpencil, kolaborasi ini juga melibatkan kader dan relawan kesehatan yang mengenal konteks lokal. Menurut WHO (2023), 60% intervensi penyakit kronis yang berhasil bersumber dari tim kolaboratif berbasis komunitas, bukan dari intervensi klinis individual semata.
Pada tahap pengelolaan terintegrasi, peran lintas profesi menjadi lebih kompleks.
Di sinilah dibutuhkan protokol layanan terpadu yang mengatur siapa melakukan apa dan kapan. Ahli Kesehatan masyarakat berperan penting dalam menyusun SOP bersama yang mengintegrasikan layanan medis, rehabilitasi, gizi, dan rujukan sosial. Studi dari Brasil menunjukkan bahwa tim multidisiplin berbasis komunitas yang dipimpin oleh pakar kesehatan masyarakat mampu menurunkan angka rawat inap akibat penyakit kronik hingga 24% dalam lima tahun (Macinko et al., 2018).
Di Indonesia, pendekatan serupa mulai diterapkan di beberapa wilayah seperti Yogyakarta dan Jawa Barat dengan hasil positif, terutama dalam pengendalian diabetes. Aspek penting lainnya adalah penguatan sistem rujukan dan dukungan sosial yang dipimpin oleh tim IPC. Sering kali pasien katastropik memerlukan layanan berlapis: dari klinik, rumah sakit, hingga dukungan di rumah pasca pengobatan.
IPC memungkinkan sistem rujukan yang dua arah, dengan umpan balik antar profesi secara rutin. Di sinilah peran petugas promosi kesehatan, pekerja sosial, dan penggerak komunitas sangat krusial. Tanpa dukungan sosial dan edukasi berkelanjutan, pasien berisiko putus pengobatan dan kembali jatuh sakit. Di Australia dan Inggris, model Community Health Hub yang memadukan layanan medis, farmasi, rehabilitasi, dan promosi kesehatan dalam satu sistem telah terbukti meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pasien (Bambra et al., 2016).
Terakhir, IPC bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi juga soal evaluasi tim secara berkelanjutan. Tim yang baik adalah tim yang belajar dari datanya sendiri. Ahli Kesehatan masyarakat berperan dalam mengembangkan indikator evaluasi berbasis tim, seperti pengendalian tekanan darah, tingkat kepatuhan terapi, dan kepuasan pasien. Di Ontario, Kanada, pendekatan ini mengurangi rawat inap akibat diabetes hingga 21% (Wodchis et al., 2015). Di Indonesia, BPJS Kesehatan telah memulai pelacakan capaian tim IPC di FKTP, seperti di Jawa Tengah. Evaluasi berbasis tim bukan hanya meningkatkan akuntabilitas, tapi juga memperkuat kohesi dan semangat kolaboratif di lapangan karena semua tahu, mereka sedang bekerja untuk tujuan yang sama.
IPC Ditanamkan Sejak Dini
Interprofessional Collaboration (IPC) bukanlah keterampilan teknis yang muncul secara otomatis saat tenaga kesehatan mulai bekerja. Kolaborasi lintas profesi adalah kompetensi sosial dan profesional yang harus ditanamkan sejak dini, khususnya sejak mahasiswa menempuh pendidikan tinggi. Namun sayangnya, sebagian besar institusi pendidikan kesehatan di Indonesia masih mengembangkan mahasiswanya dalam sekat-sekat keilmuan. Mahasiswa kedokteran belajar sendiri, mahasiswa keperawatan, farmasi, gizi, dan kesehatan masyarakat pun berada di ruang-ruang terpisah.
Padahal, pasien di lapangan tidak membutuhkan satu profesi, melainkan tim yang solid. Maka, kampus seharusnya menjadi tempat pertama bagi calon tenaga kesehatan untuk belajar bekerja dalam tim lintas disiplin.
Untuk itu, pendidikan interprofesi harus dimulai dari desain fisik dan tata ruang kampus. Kampus kesehatan seharusnya tidak dibangun dengan blok-blok fakultas yang terisolasi, melainkan dengan gedung kuliah bersama antarprogram studi kesehatan, laboratorium terpadu, dan ruang diskusi kolaboratif yang mendorong pertemuan lintas mahasiswa.
Desain ruang menentukan desain pikiran jika ruang dibangun untuk berkolaborasi, maka identitas profesional mahasiswa juga akan terbentuk dalam semangat kerja sama. Beberapa universitas besar di dunia seperti University of Toronto dan Monash University telah membuktikan bahwa desain fisik kampus yang terintegrasi mendorong budaya IPC lebih kuat dibanding sistem pendidikan yang sektoral dan eksklusif.
Selain aspek fisik, hal yang lebih esensial adalah perencanaan kurikulum interprofesi. Program studi dalam rumpun kesehatan perlu menyusun mata kuliah bersama, modul kasus interprofesi, praktikum lintas prodi, hingga kegiatan pengabdian masyarakat kolaboratif. Dalam setiap kesempatan pembelajaran, mahasiswa harus diajak menyelesaikan masalah kesehatan secara tim misalnya merancang rencana intervensi untuk pasien diabetes dengan melibatkan pemikiran dokter, ahli gizi, perawat, dan promotor kesehatan secara simultan. Ini bukan sekadar latihan akademik, melainkan latihan dunia nyata yang menciptakan calon-calon profesional yang mampu memahami batas dan kekuatan peran dirinya serta orang lain.
Agar memiliki dampak luas dan berkelanjutan, semangat IPC ini harus tertanam dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pendidikan, IPC menjadi bagian dari kompetensi lulusan. Dalam bidang penelitian, riset-riset kolaboratif antarprodi menjadi standar inovasi. Dan dalam bidang pengabdian, tim interprofesi diturunkan bersama ke masyarakat untuk mengintervensi masalah kesehatan riil secara terpadu. Dengan menjadikan IPC sebagai jiwa dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka PT benar-benar mempersiapkan lulusannya bukan hanya menjadi ahli di bidangnya saja, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk bermitra secara kolaboratif dalam sistem kesehatan yang kompleks dan dinamis. Insya Allah.
(Oleh: Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph. D, Ketua IAKMI Sumut & Dosen FKM USU).

 3 months ago
95
3 months ago
95