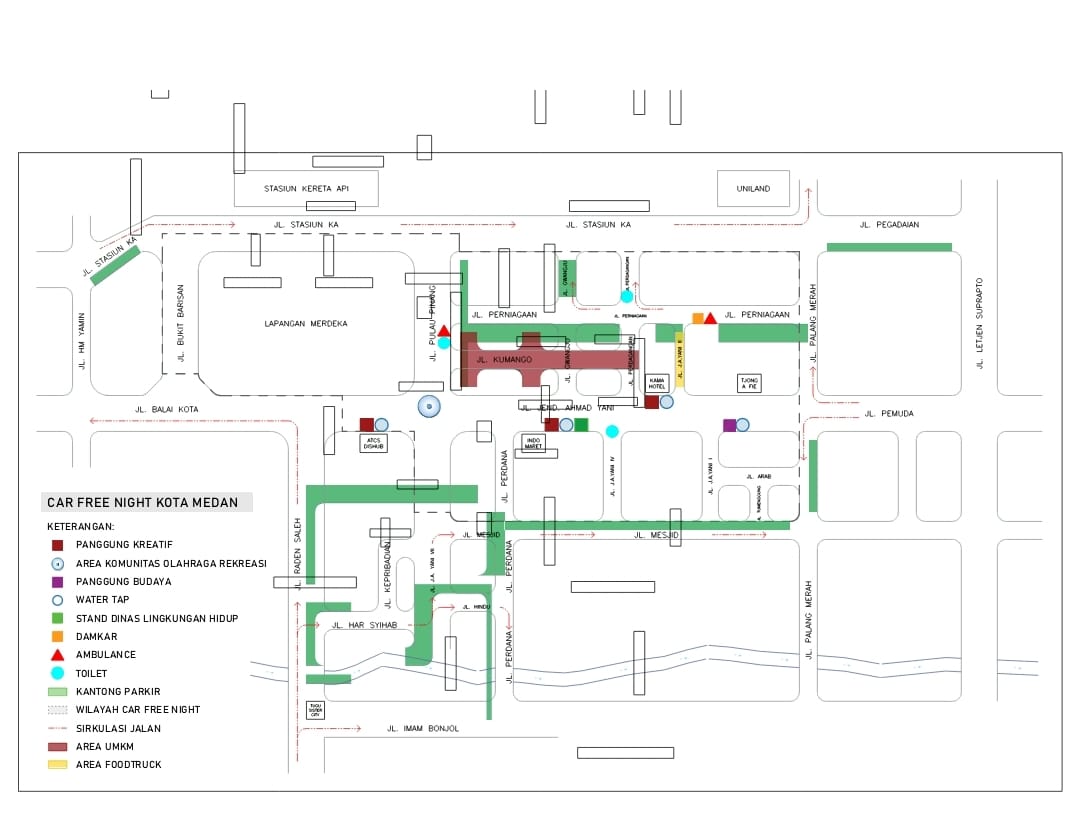SUMUTPOS.CO – Di tengah komitmen nasional untuk mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030, Provinsi Sumatera Utara masih dihadapkan pada tantangan besar.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria, suatu kabupaten/kota baru dapat dinyatakan eliminasi malaria jika tidak ditemukan kasus penularan lokal (indigenous) selama tiga tahun berturut-turut, memiliki sistem surveilans yang andal, serta menunjukkan cakupan pemeriksaan dan pengobatan kasus yang memenuhi standar nasional.
Namun hingga kini, terdapat sepuluh daerah di Sumatera Utara yang belum memenuhi syarat tersebut, yaitu Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, Gunungsitoli, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Langkat.

Kondisi ini tidak hanya menggambarkan tantangan teknis dalam pengendalian penyakit, tetapi juga menunjukkan ketimpangan struktural dalam dukungan antardaerah. Nias Selatan misalnya, harus memperpanjang status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria hingga Maret 2025 akibat masih munculnya kasus baru.
Namun di sisi lain, penetapan maupun pencabutan status KLB tidak selalu konsisten dan seringkali tidak diiringi dengan dukungan pendanaan atau teknis yang memadai dari pusat. Ketika status KLB dicabut tanpa penyelesaian tuntas, maka beban penanganan seolah beralih sepenuhnya ke pemerintah daerah dan bahkan desa yang belum tentu memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah komitmen eliminasi malaria akan ditegakkan bersama, atau dibiarkan menjadi beban sepihak di level paling bawah?
Penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) seharusnya menjadi bentuk respons cepat dan terukur terhadap situasi wabah. Namun di lapangan, implementasinya tidak berlaku secara merata.
Beberapa daerah seperti Nias Selatan mendapatkan penetapan resmi KLB, sementara daerah lain yang memiliki situasi epidemiologis serupa justru tidak memperoleh status yang sama. Ketimpangan ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota yang sedang berjibaku dengan lonjakan kasus namun tidak mendapat perlakuan prioritas.
Yang lebih mengkhawatirkan, status KLB di sejumlah wilayah terancam dicabut bukan karena kasus telah terkendali, melainkan karena lemahnya koordinasi dan minimnya intervensi lanjutan dari pemerintah pusat. Jika status KLB dihentikan tanpa penyelesaian yang menyeluruh, maka risiko terbesar bukan hanya pada naiknya kembali kasus, tetapi juga pada menghilangnya tanggung jawab pusat terhadap daerah yang masih membutuhkan dukungan.
Janji pemerintah pusat untuk menurunkan bantuan, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Di beberapa daerah, dana belum juga cair, sementara petugas kesehatan di lapangan harus tetap berjalan dengan sumber daya terbatas. Ketidakhadiran dukungan konkret ini memperlemah semangat gotong royong yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat kesehatan masyarakat.
Mengapa Sumut Belum Mampu Eliminasi Malaria?
Upaya eliminasi malaria di Sumatera Utara menghadapi tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Dari sisi kesehatan masyarakat, distribusi tenaga kesehatan masih belum merata lebih dari 47% puskesmas belum memiliki formasi tenaga lengkap, dan sebagian besar wilayah endemis justru berada di daerah dengan akses layanan terbatas. Hal ini berdampak pada lemahnya deteksi dini, surveilans aktif, dan pelayanan pengobatan yang cepat dan tepat.
Secara epidemiologis, Sumatera Utara masih memiliki wilayah dengan API (Annual Parasite Incidence) tinggi seperti Batu Bara (2,29), Labuhanbatu Utara (1,19), dan Asahan (1,08). Penularan lokal (indigenous) masih terjadi, yang menandakan bahwa rantai penularan belum berhasil diputus. Ini diperparah dengan mobilitas penduduk antar wilayah dan kurangnya pengawasan terhadap kasus import.
Dari aspek kesehatan lingkungan, masih banyak desa di daerah endemis yang memiliki kondisi sanitasi buruk, genangan air, dan tempat perindukan nyamuk yang tidak tertangani. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi layak masih rendah, terutama di wilayah kepulauan dan pegunungan seperti Nias dan Mandailing Natal. Upaya vector control sering bersifat insidental, bukan bagian dari strategi berkelanjutan.
Berikutnya, kegiatan konversi lahan menjadi perkebunan sawit di Sumatera Utara turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko malaria. Perubahan lanskap ini menciptakan habitat baru bagi nyamuk vektor seperti Anopheles, terutama melalui genangan air di parit dan kanal perkebunan.
Selain itu, mobilitas pekerja dari daerah endemis dan minimnya infrastruktur sanitasi di pemukiman sekitar kebun memperbesar potensi penularan. Tanpa intervensi lintas sektor yang melibatkan perusahaan perkebunan, upaya eliminasi malaria akan terus menghadapi tantangan dari sisi ekologi dan sosial.
Kemudian, aspek promosi kesehatan juga belum optimal. Banyak masyarakat belum memahami gejala awal malaria, belum melakukan upaya pencegahan mandiri seperti penggunaan kelambu, dan tidak terbiasa mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan saat demam. Masih ada kesenjangan antara kampanye tingkat provinsi dan pemahaman di akar rumput, terutama di desa-desa terpencil.
Dan terakhir, perubahan iklim memperburuk situasi. Pola hujan yang tidak menentu, kenaikan suhu, dan peningkatan kelembapan memperluas habitat vektor nyamuk Anopheles dan memperpanjang masa hidupnya. Daerah yang sebelumnya rendah risiko kini menjadi wilayah potensial penularan, sementara sistem kesehatan belum siap beradaptasi dengan dinamika baru ini.
Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa eliminasi malaria bukan sekadar persoalan medis, tapi juga urusan tata kelola, literasi masyarakat, dan kepekaan terhadap dinamika lingkungan. Tanpa strategi lintas sektor yang adaptif, Sumatera Utara akan terus berada dalam siklus penanggulangan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Komitmen Nasional Tak Boleh Sebatas Dokumen
Pemerintah pusat sejatinya telah menetapkan komitmen yang kuat untuk eliminasi malaria secara nasional pada tahun 2030. Komitmen ini bukan hanya slogan, melainkan telah dituangkan dalam berbagai kebijakan strategis seperti Rencana Aksi Nasional Eliminasi Malaria (RAN-EM) 2020–2024, yang menargetkan seluruh kabupaten/kota bebas malaria dalam waktu kurang dari satu dekade.
Dalam rencana tersebut, daerah seharusnya tidak berjalan sendiri. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, memiliki mandat untuk mendampingi, mendistribusikan obat, kelambu, dan pelatihan tenaga surveilans, termasuk dalam menghadapi lonjakan kasus atau status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Lebih dari itu, Indonesia adalah bagian dari aliansi regional seperti Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) dan telah berkomitmen dalam Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengakhiri epidemi malaria pada tahun 2030.
Artinya, apa yang terjadi di Kepulauan Nias, Labuhanbatu Utara, hingga Batu Bara bukan hanya persoalan lokal, tetapi bagian dari reputasi dan kredibilitas Indonesia dalam skala global.
Ketika status KLB terancam dicabut karena alasan administratif atau lambatnya pencairan dana pusat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa masyarakat desa—tetapi juga kegagalan negara memenuhi janji globalnya.
Maka menjadi tidak masuk akal jika beban penanggulangan malaria hanya dibebankan pada kepala daerah dan desa, dengan instruksi penggunaan dana desa tanpa pendampingan dan tanpa regulasi teknis yang jelas. Situasi ini menunjukkan inkonsistensi: pusat ingin target tercapai, tapi beban sepenuhnya diserahkan pada daerah yang minim kapasitas fiskal dan sumber daya manusia.
Solusi Konkret untuk Sumut
Bagi Provinsi Sumatera Utara, solusi eliminasi malaria harus dirancang dengan mempertimbangkan realitas wilayah yang sangat beragam mulai dari kota besar seperti Medan hingga wilayah kepulauan dan pegunungan yang sulit dijangkau seperti Nias Selatan, Mandailing Natal, atau Labuhanbatu Raya. Karena itu, pendekatan “satu kebijakan untuk semua” jelas tidak lagi memadai.
Pertama, pemerintah provinsi perlu mendorong lahirnya kebijakan turunan berupa peraturan gubernur atau surat edaran teknis yang menguatkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan penanggulangan malaria. Payung hukum ini penting agar kepala desa tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran untuk surveilans aktif, pelatihan kader, pengadaan alat deteksi dini, maupun operasional kegiatan preventif di masyarakat.
Kedua, Sumatera Utara perlu membentuk Tim Teknis Eliminasi Malaria Provinsi yang fokus pada pendampingan kabupaten/kota yang belum eliminasi. Tim ini harus mampu menjembatani koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Keuangan Daerah, sehingga program berbasis desa benar-benar dapat berjalan dengan baik dan terukur.
Ketiga, keterlibatan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat dalam bentuk klinik desa sehat, riset operasional, dan pelatihan kader malaria berbasis lokalitas. Model kolaborasi ini terbukti efektif dalam konteks daerah lain dan bisa direplikasi di Sumut dengan pendekatan partisipatif.
Terakhir, peran pemerintah pusat tetap tidak bisa dilepaskan. Sumatera Utara, sebagai provinsi dengan wilayah kepulauan, membutuhkan skema afirmatif dari pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan untuk eliminasi malaria, maupun penugasan khusus dari Kemenkes, BNPB, dan Kemendagri agar desa-desa tidak dibiarkan menanggung beban sendiri. Inshaallah.
(oleh: Destanul Aulia, Tenaga Ahli Dinas Kesehatan Sumut dan Dosen FKM USU).

 2 months ago
70
2 months ago
70