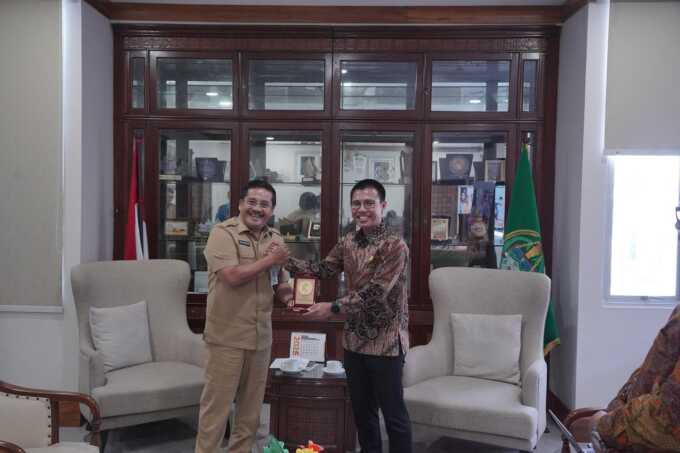Oleh: Pdt. Penrad Siagian
Disahkannya revisi Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025 oleh DPR RI, memperlihatkan bukan hanya pelanggaran prosedur penyusunan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat dan mandat reformasi dalam pemberantasan korupsi.
Wajah Undang-Undang yang Inkonstitusional
Secara prosedural, pengesahan UU BUMN cacat formil. Minimnya partisipasi publik dan tidak adanya transparansi membuat produk hukum ini layak disebut inkonstitusional. Mengacu pada Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, DPR dan Pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun cetak agar tersedia ruang untuk masukan dan tanggapan. Kewajiban ini berlaku sejak tahap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan RUU, hingga pengundangan UU.
Pasal 96 UU yang sama menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pada ayat (4) ditegaskan bahwa masyarakat wajib diberi kemudahan dalam mengakses naskah akademik maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.
Hal lain yang patut disorot adalah fakta bahwa revisi ini merupakan produk hukum pertama yang lahir di awal masa sidang paripurna DPR RI tahun 2025. RUU ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan maupun carry over dari tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang urgensi dan justifikasi pembahasannya di awal tahun, serta mengapa menjadi produk legislasi pertama DPR RI periode 2024–2029.
Lebih dari sekadar inkonstitusional, pengesahan ini mencerminkan pengkhianatan terhadap penegakan hukum dan semangat antikorupsi. Artinya, DPR telah mengingkari amanat reformasi dan kepercayaan rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat konstitusional.
Mengkebiri Semangat Antikorupsi
Semangat antikorupsi tampaknya semakin terpinggirkan dari tubuh lembaga yang menyebut diri sebagai perwakilan rakyat ini. Revisi UU BUMN memperlihatkan indikasi kuat pengaburan prinsip akuntabilitas. Sejumlah pasal dalam revisi ini tidak hanya berpotensi melanggengkan praktik korupsi di BUMN, tetapi juga menyulitkan, bahkan menghalangi, upaya penegakan hukum.
Kritik terhadap UU No. 1 Tahun 2025
Setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan revisi UU BUMN ini melemahkan semangat antikorupsi:
Pertama, pemangkasan fungsi pengawasan terhadap BUMN. Misalnya, pada Pasal 71 UU BUMN sebelumnya, BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Namun dalam UU hasil revisi, BPK hanya dapat melakukan PDTT dan itupun harus atas permintaan alat kelengkapan DPR. Hal ini membuka ruang politisasi terhadap fungsi pengawasan yang seharusnya profesional dan bebas dari konflik kepentingan. PDTT yang selama ini menjadi alat BPK dalam mengungkap indikasi kerugian negara dan unsur pidana kini perlu “restu” politik terlebih dahulu.
Kedua, pada pasal 3X ayat (1) dan Pasal 9G dinyatakan bahwa organ penyelenggara BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Implikasinya, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN—kecuali memenuhi syarat kerugian negara di atas Rp1 miliar dan melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan demikian, celah hukum untuk melindungi koruptor di BUMN makin terbuka lebar.
Ketiga, dihapusnya frasa “yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” dari definisi BUMN. Ini berarti dana yang diberikan negara kepada BUMN tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara. Konsekuensinya, kekayaan BUMN tidak termasuk dalam kategori keuangan negara, yang artinya luput dari pengawasan hukum negara. Padahal, justru di titik inilah potensi penyalahgunaan anggaran terbesar bisa terjadi.
Ketentuan-ketentuan tersebut, mulai dari pemisahan kekayaan negara hingga penurunan status pejabat BUMN dari pejabat publik, justru memberikan imunitas bagi siapa pun yang ingin menyalahgunakan kewenangan dan melakukan suap di lingkungan BUMN.
Sebagai perwakilan rakyat daerah, saya mempertanyakan revisi UU BUMN ini: untuk siapa sebenarnya undang-undang ini dibuat? Wajah legislasi yang abnormal, substansi yang bertentangan dengan kepentingan negara dan rakyat, serta kejanggalan proses pengesahan menjadi bukti bahwa revisi ini bukan untuk kepentingan publik. DPR RI seolah tergopoh-gopoh ingin mengesahkan produk hukum ini—sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru ditinggalkan.
*) Anggota DPD RI-MPR RI
Oleh: Pdt. Penrad Siagian
Disahkannya revisi Undang-Undang BUMN No. 19 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025 pada 4 Februari 2025 oleh DPR RI, memperlihatkan bukan hanya pelanggaran prosedur penyusunan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat dan mandat reformasi dalam pemberantasan korupsi.
Wajah Undang-Undang yang Inkonstitusional

Secara prosedural, pengesahan UU BUMN cacat formil. Minimnya partisipasi publik dan tidak adanya transparansi membuat produk hukum ini layak disebut inkonstitusional. Mengacu pada Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, DPR dan Pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik maupun cetak agar tersedia ruang untuk masukan dan tanggapan. Kewajiban ini berlaku sejak tahap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan RUU, hingga pengundangan UU.
Pasal 96 UU yang sama menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pada ayat (4) ditegaskan bahwa masyarakat wajib diberi kemudahan dalam mengakses naskah akademik maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.
Hal lain yang patut disorot adalah fakta bahwa revisi ini merupakan produk hukum pertama yang lahir di awal masa sidang paripurna DPR RI tahun 2025. RUU ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan maupun carry over dari tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang urgensi dan justifikasi pembahasannya di awal tahun, serta mengapa menjadi produk legislasi pertama DPR RI periode 2024–2029.
Lebih dari sekadar inkonstitusional, pengesahan ini mencerminkan pengkhianatan terhadap penegakan hukum dan semangat antikorupsi. Artinya, DPR telah mengingkari amanat reformasi dan kepercayaan rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat konstitusional.
Mengkebiri Semangat Antikorupsi
Semangat antikorupsi tampaknya semakin terpinggirkan dari tubuh lembaga yang menyebut diri sebagai perwakilan rakyat ini. Revisi UU BUMN memperlihatkan indikasi kuat pengaburan prinsip akuntabilitas. Sejumlah pasal dalam revisi ini tidak hanya berpotensi melanggengkan praktik korupsi di BUMN, tetapi juga menyulitkan, bahkan menghalangi, upaya penegakan hukum.
Kritik terhadap UU No. 1 Tahun 2025
Setidaknya ada tiga poin krusial yang menunjukkan revisi UU BUMN ini melemahkan semangat antikorupsi:
Pertama, pemangkasan fungsi pengawasan terhadap BUMN. Misalnya, pada Pasal 71 UU BUMN sebelumnya, BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Namun dalam UU hasil revisi, BPK hanya dapat melakukan PDTT dan itupun harus atas permintaan alat kelengkapan DPR. Hal ini membuka ruang politisasi terhadap fungsi pengawasan yang seharusnya profesional dan bebas dari konflik kepentingan. PDTT yang selama ini menjadi alat BPK dalam mengungkap indikasi kerugian negara dan unsur pidana kini perlu “restu” politik terlebih dahulu.
Kedua, pada pasal 3X ayat (1) dan Pasal 9G dinyatakan bahwa organ penyelenggara BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Implikasinya, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN—kecuali memenuhi syarat kerugian negara di atas Rp1 miliar dan melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan demikian, celah hukum untuk melindungi koruptor di BUMN makin terbuka lebar.
Ketiga, dihapusnya frasa “yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” dari definisi BUMN. Ini berarti dana yang diberikan negara kepada BUMN tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara. Konsekuensinya, kekayaan BUMN tidak termasuk dalam kategori keuangan negara, yang artinya luput dari pengawasan hukum negara. Padahal, justru di titik inilah potensi penyalahgunaan anggaran terbesar bisa terjadi.
Ketentuan-ketentuan tersebut, mulai dari pemisahan kekayaan negara hingga penurunan status pejabat BUMN dari pejabat publik, justru memberikan imunitas bagi siapa pun yang ingin menyalahgunakan kewenangan dan melakukan suap di lingkungan BUMN.
Sebagai perwakilan rakyat daerah, saya mempertanyakan revisi UU BUMN ini: untuk siapa sebenarnya undang-undang ini dibuat? Wajah legislasi yang abnormal, substansi yang bertentangan dengan kepentingan negara dan rakyat, serta kejanggalan proses pengesahan menjadi bukti bahwa revisi ini bukan untuk kepentingan publik. DPR RI seolah tergopoh-gopoh ingin mengesahkan produk hukum ini—sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru ditinggalkan.
*) Anggota DPD RI-MPR RI

 3 months ago
53
3 months ago
53